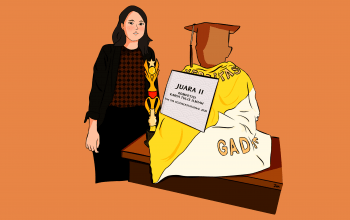“The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.”
― Carl R. Rogers
Tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara, seorang bapak pendidikan nasional, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Ki Hadjar Dewantoro yang terkenal dengan semboyan “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” mempunyai cita-cita untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, sebab pada masa kolonial dahulu hanya anak-anak Belanda dan orang kaya saja yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan.
Namun, kita sadari bahwa peringatan Hardiknas pada tahun ini belum bisa menjadi sebuah perayaan yang menggembirakan melainkan sebagai sebuah perenungan. Bukan karena semua persoalan itu baru-baru saja terjadi di tahun-tahun belakangan ini melainkan karena kumulasi dari semua persoalan yang pernah terjadi.
Sampai saat ini masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, antara lain standar fasilitas pendidikan yang tidak merata dan sistem pendidikan yang masih berubah-ubah menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam menentukan arah dari pendidikan yang dianut para siswa, serta masih terdapat banyaknya kritik dari berbagai kalangan perihal sistem pendidikan yang ada namun tidak ada reaksi dari kementerian terkait menunjukkan ketidakpekaan pemerintah atas kondisi faktual dalam masyarakat.
Setidaknya terdapat 3 perenungan yang mesti mendapat porsi perhatian dari pemerintah.
Mengingat pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sisem pendidikan nasional, yang mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kecerdasan sendiri berdasarkan teori ‘Multiple Intelligence’ oleh Howard Gardner terdiri dari 8 unsur yang berbeda-beda komposisinya pada setiap orang. Stephen Jay Gould, seorang paleontolog asal Amerika, mengemukakan bahwa kecerdasan sebenarnya tak bisa diukur, dan juga mempertanyakan sudut pandang hereditarian atas kecerdasan.
Dengan diterapkannya Ujian Nasional dan sistem ranking untuk menentukan kelulusan dan kepintaran siswa, para siswa secara tidak sengaja akan didorong untuk mengedepankan hasil akhir, dan penilaian mengenai kecerdasan mereka akan dipangkas ke dalam suatu dimensi yang ditekankan oleh kurikulum yang ditentukan pemerintah. Siswa tidak diajak untuk mengembangkan potensi dan karakter khusus yang dimiliki oleh diri mereka masing-masing. Menurut Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada sebuah diskusi yang diulas dalam Kompas, ada yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia menilai pendidikan lebih menitikberatkan kecerdasan kognitif dan melupakan kecerdasan emosional. Tolok ukur kecerdasan terletak pada nilai hasil ujian, bukan pada proses siswa mendapatkan nilai tersebut. Maka wajar saja walau siswa dapat mengerjakan berbagai macam soal, ke depan ia belum tentu mampu untuk berkembang dan berubah menjadi manusia yang arif.
Indonesia sejatinya tidak perlu menyamai dan membandingkan sistem pendidikannya dengan sistem yang dianut oleh negara lain, sebab bagi Ki Hadjar Dewantara sendiri sistem yang paling cocok bagi Indonesia adalah ‘tut wuri handhayani’ bahwa dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, bukan memberikan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh para siswa untuk diakui sebagai manusia yang cerdas.
Peristiwa yang mesti menjadi perenungan kedua adalah timbulnya pemikiran bahwa perkembangan pendidikan hanya dipusatkan di pulau Jawa. Padahal jika kita melihat pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” serta dalam Pasal 53 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Hal ini dirasakan oleh masyarakat di luar pulau Jawa bahwa fasilitas pendidikan sekolah-sekolah di luar Jawa begitu kurang, staff pengajar yang tidak memadahi, kemudian keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi dan buku penunjang pendidikan, serta desakan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka cenderung meninggalkan sekolah untuk mencari nafkah.
Ketiga, yang menjadi sebuah tamparan keras bagi para orang tua bahwa banyak anak rupanya menjadi korban kekerasan terlebih kekerasan seksual oleh staff pengajar dan pekerja di sekolahnya. Terungkapnya suatu kasus membuka pintu kasus lain, tahu-tahu sudah begitu banyak kasus terungkap yang selama ini dipendam karena rasa malu dan takut.
Padahal jika kita melihat pada pasal 54 UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa, “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”
Sekolah semestinya menjadi tempat di mana orang tua bisa merasa aman karena telah menitipkan anaknya untuk mendapat pendidikan supaya menjadi manusia yang lebih bermanfaat, cerdas dan arif ketika dewasa kelak. Dengan adanya kasus tersebut tentu saja menimbulkan keraguan bagi orang tua untuk menitipkan anaknya di sekolah, belum lagi kekhawatiran akan adanya penculik, pemeras, penganiaya, pembunuh, bahkan predator pedofilia setiap kali melepas anaknya untuk pergi bersekolah.
Masih banyak yang perlu dijadikan sebagai sebuah perenungan pada Hardiknas tahun 2014 ini. Pemerintah harus memberikan perhatian besar serta menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam memajukan bangsa ini sebab kelak pelajar-pelajar ini akan menjadi penerus bangsa. Tidak akan ada yang berubah ketika pemerintah cenderung memusatkan perhatiannya pada tindakan represif, sedangkan tidak mengupayakan tindakan preventif pada pondasi dasarnya.