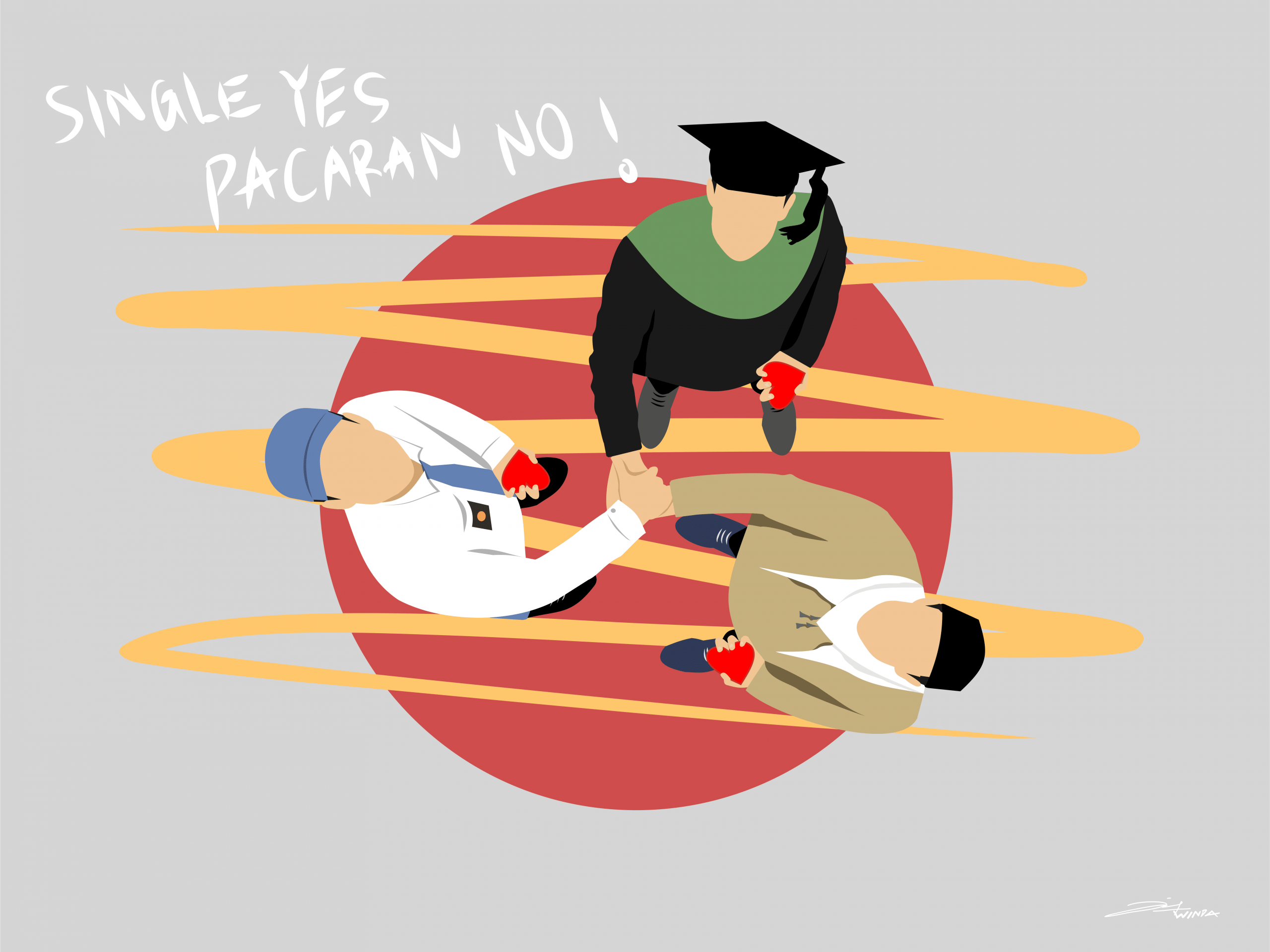Bagi sebagian orang, hidup akan lebih berwarna kalau bisa punya pacar. Jalan sore di Wisdom Park seberang Fakultas Hukum, makan siang bareng di Pusat Jajanan Lembah (Pujale), ataupun belajar dan mengerjakan tiap tugas bersama-sama di perpustakaan. Atau kita bisa ambil contoh yang lebih elit daripada itu, seperti jalan-jalan ke mall yang tidak jauh dari kampus, jajan di restoran ternama, ataupun belajar bareng di warung kopi berbintang lima.
Sebagian lain ada yang ingin berpacaran namun kebetulan belum berkesempatan (baca: masih jomblo). Beruntunglah bagi mereka yang berbahagia dalam pacaran, terkhusus karena hal yang sederhana, seperti melihat senyuman mbaknya atau mendengar rayuan mas’e, misalnya.
Di samping mereka yang memilih mengisi sebagian masa mudanya –sembari mencari jodoh– dengan cara berpacaran, di seberang jalan ada orang-orang yang dengan teguh tegap memilih untuk tidak pacaran. Memilih untuk tidak berpacaran juga merupakan sebuah jalan, kan?
Mereka yang memilih untuk tidak pacaran dapat dibagi dalam tiga golongan. Ada orang yang tidak pacaran karena alasan praktis, alasan agamis, hingga alasan filosofis. Tiap-tiap golongan ini tentu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam memaknai pilihan mereka. Jalan ninja (baca: pilihan hidup) mereka sebagai jomblo diwarnai dengan api semangat yang berbeda-beda!
Golongan Santuy-isme
Golongan pertama dilandasi pemikiran yang sederhana dan praktis ketika memilih tidak pacaran. Misalnya, “Pacaran cuma buang-buang waktu”, atau “Buang-buang duit aja, ah!”, tak lupa alasan paling klasik, “Mau fokus belajar dulu, hehe”. Mereka melandasinya dengan hal-hal yang praktis sehingga tidak mau ambil pusing.
Dalam golongan pertama ini tak jarang juga dijumpai fakboi yang melandasi pemikirannya untuk tidak pacaran dengan alasan di atas pemikiran rata-rata manusia –yang sebenarnya ngeselin– seperti, “Biar ga terikat sama satu cewe, jadi bisa deketin sana-sini”, begitu katanya…. Hilihhh…
Sikap golongan pertama ini biasanya lebih santuy terhadap mereka yang berpacaran. “Yaudah, lu ya elu, gue ya gue. Gapapa kok lu pada pacaran”, ucap seorang teman yang termasuk golongan ini ketika ia sedang rebahan. Sepertinya tidak berlebihan juga kalau saya menyebutnya golongan santuy-isme. Hehehe.
Golongan Hijrahers
Golongan ini sepertinya yang paling banyak muncul di permukaan. Argumen utamanya adalah Wa la taqrabuz-zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Biasanya pada masa awal transisi dalam berhijrah (berpindah ke pribadi yang lebih baik), pacaran menjadi salah satu topik yang gencar dibahas.
Berbeda dengan mereka yang sudah hijrah sejak lama –yang sudah tidak begitu gencar membahas pacaran–, hijrahers baru ini cenderung sedang asyik-asyiknya menyerukan kepada orang lain untuk berhenti pacaran. Fenomena ini paling jelas rupanya bisa terlihat dalam gerakan anti-pacaran yang masif mengadakan seminar rutin hingga menjual berbagai produk berisi ajakan sejenis “single yes, pacaran no!” yang bisa berupa pin, stiker, topi, masker, jilbab, dan kaos –sampai kalau perlu semua perabot rumah tangga dijadikan merchandise kemudian dijual ke seluruh pelosok nusantara untuk modal nikah muda. Hiya hiya hiyaaa~
Pacaran yang dinilai sebagai suatu manifestasi zina biasanya berlandaskan pengandaian bahwa dengan pacaran seseorang bisa berbuat berbagai bentuk zina, seperti menatap mata lawan jenis –yang karena olehnya menyebabkan pikiran kotor–, berpegangan tangan, berangkulan dan berpelukan, berciuman, hingga hubungan seksual.
Landasan ini tentulah sangat bernilai besar dan bertujuan baik. Dan tentu, saya sangat menghargai dan menghormati maksud baik ini. Namun, hal yang perlu dikritisi adalah: tidak semudah itu, Ferguso! Kita tidak bisa menerima pemahaman bahwa semua yang berpacaran berbuat zina begitu saja secara dogmatif dan ikut-ikutan –seperti membebek berteriak kuminis itu ateis–, melainkan harus pula menyelidiki lebih lanjut.
Kalau kita melihat fenomena ini melalui kacamata prinsip falsifikasi Karl Popper, maka segala hipotesa tidak bisa dianggap selalu benar selama masih ada celah untuk diadakan falsifikasi. Suatu pernyataan rasional harus selalu terbuka untuk difalsifikasi. Contoh sederhana diberikan oleh Romo Magnis-Suseno dalam Menalar Tuhan (2006) sebagai berikut:
“Semua gagak berwarna hitam” merupakan pernyataan yang rasional yang dapat difalsifikasi apabila “ada gagak berwarna non-hitam.” Cara falsifikasinya: melihat apakah ada burung gagak berwarna hitam atau tidak. Kita dapat mengetahui bahwa seluruh burung gagak berwarna hitam, tapi akan selalu ada kemungkinan bahwa di masa depan akan ada gagak berwarna non-hitam.
Dalam kaitannya dengan pacaran, secara sederhana dapat dituliskan begini, “semua yang berpacaran berbuat zina” dapat difalsifikasi apabila “ada orang yang berpacaran tanpa berbuat zina.” Pernyataan “semua yang berpacaran berbuat zina” merupakan pernyataan yang diverifikasi berdasarkan satu peristiwa tertentu, bukan berdasarkan sebuah hukum yang berlaku umum.
Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis semua yang berpacaran berbuat zina bukan merupakan suatu kebenaran absolut, karena dapat difalsifikasi dengan kemungkinan bahwa bisa jadi ada orang yang berpacaran tanpa berbuat zina.
Gerakan anti-pacaran ini juga sering kali memberi solusi atas penolakannya terhadap pacaran dengan menganjurkan nikah muda. Namun, perlu lagi dipertimbangkan apakah nikah muda memang merupakan solusi terbaik?
Mengutip tirto.id, berdasarkan laporan UNICEF dan BPS yang dirilis awal tahun 2016 berjudul “Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, Indonesia termasuk sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia dan menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Hal ini memberi kita pertanyaan, apakah di usia kurang dari 20 tahun kondisi emosional dan finansial seseorang sudah matang untuk berumah tangga?
Kembali pada pemaknaan antara pacaran dan zina, setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing soal tolak ukur zina, terkhusus soal batasan tentang kedekatan dengan lawan jenis. Hal terpenting adalah mempertahankan prinsip-prinsip kita dengan mempertanggungjawabkannya secara rasional dan bukan sekedar ikut-ikutan.
Hormat saya bagi mereka yang dapat mempertanggungjawabkan pilihannya untuk tidak pacaran secara konsisten dan rasional, serta dapat menghargai pilihan orang lain yang berbeda.
Sebaliknya, lucu juga rasanya kalau sampai ternyata ada orang yang mengaku ‘anti-pacaran’ tetapi masih PDKT dengan chat lawan jenis tengah malam untuk sekedar basa-basi (baca: ‘modus’) yang dibungkus pesan mengingatkan shalat atau foto berdua macam model pre-wedding sambil memberi caption bucin beserta sensor pada wajah masing-masing. Hmmm…
Wahai anak muda, sesungguhnya pacaran atau tidak pacaran itu bukan hanya soal urusan formil –”Aku suka kamu, kita pacaran, yuk!“–, namun juga soal substansi menyangkut apa yang antum lakukan di dalamnya. Kalau Akhi dan Ukhti sekalian mengaku tidak mau pacaran namun berkegiatan layaknya orang berpacaran, lantas apa bedanya dengan orang-orang yang berpacaran di seberang antum?
Satu lagi, kalau mau menjadi jomblo, monggo saja. Tak perlu susah payah men-judge pilihan orang lain yang berpacaran atau repot-repot mampir berkomentar “Maaf sekedar mengingatkan!” sehingga merasa diri sendiri lebih baik. Apalagi kalau sampai mengurus soal surga dan neraka orang lain. Memangnya situ panitia hari kiamat?
Golongan Para ‘Filsuf’
Golongan terakhir ini biasanya banyak mempertanyakan dan meragukan apa pacaran sebenarnya, sehingga –kalau tidak berlebihan– mirip seperti ‘filsuf’ karena perenungan dan keingintahuannya itu.
Biasanya golongan ini selalu mengkritisi dengan begitu mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang lugas dan diwarnai kuriositas tinggi. “Pacaran itu sebenarnya apa, sih? Apa pacaran benar-benar ada, atau justru sekedar hubungan yang semu? Apa makna pacaran itu sendiri?”, misalnya.
Selain bersikap kritis dan skeptis terhadap kaum pacaran, kaum ‘anti-pacaran’ juga jadi sasaran. Apabila kita mengatakan “saya anti-pacaran” maka secara tidak langsung kita mengandaikan bahwa pacaran itu ada –dengan menggunakan kata anti yang bermaksud menentang pacaran berarti mengandaikan bahwa pacaran itu ada–, sementara apa pacaran itu sendiri dan kegiatan yang ada di dalamnya belum terumus sebagai suatu hukum yang berlaku umum.
Permasalahan kemudian bukan lagi soal mau atau tidak mau untuk pacaran. Lebih dari itu, hal yang menjadi sorotan adalah mengenai hakikat pacaran itu sendiri. Mau atau tidak mau adalah pilihan yang dapat kita pilih apabila sebelumnya kita mengandaikan bahwa pacaran termanifestasikan dalam suatu bentuk tertentu. Namun, apa yang terjadi apabila pacaran sendiri sebenarnya dapat ditafsirkan secara berbeda-beda –bukan dalam suatu bentuk tetap tertentu– sekaligus dapat dipraktikan dengan cara yang bermacam-macam? Singkatnya, kita tidak bisa secara langsung memutuskan mau atau tidak mau berpacaran tanpa mengetahui apa pacaran itu sendiri.
Pacaran secara empiris dapat kita saksikan melalui kisah asmara sepasang kekasih yang saling mencintai dengan mengikrarkan status istimewa di antara keduanya. Namun, pemaknaan pacaran dengan segala kesepakatan yang ada di dalamnya tidak berlaku umum –dengan demikian eksistensinya mendahului esensinya, hingga menyebabkan esensinya tidak baku– sehingga harus diselidiki lebih lanjut.
Golongan terakhir ini memberikan kita sedikit PR baru soal pacaran itu sendiri. Mereka ingin melandaskan pilihannya untuk berpacaran atau tidak dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama soal apa yang ada di dalam pacaran itu sendiri.
Pengklasifikasian ketiga golongan ini juga sebenarnya hanyalah sebuah gambaran kasar berdasarkan pengalaman empiris keseharian –atau justru tidak ilmiah?– Dan dari ketiga golongan ini kita bisa sedikit merefleksikan sedikit potret kehidupan soal berbagai alasan orang memilih untuk tidak pacaran. Lebih lanjut, kita harus memahami kembali apa arti pacaran itu sendiri.
Memahami Kembali Pacaran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002:807), pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran adalah bercintaan; berkasih-kasihan (dengan pacar). Sementara itu, memacari adalah mengencani; menjadikan seseorang sebagai pacar.
Dalam menyikapi pacaran, tiap orang memiliki tafsiran sendiri tentangnya. Ada yang memahaminya sebagai hubungan menjelang pernikahan, proses penjajakan, penyemangat belajar, bahkan ajang baper-baperan hingga pamer-pameran.
Pacaran sendiri tak memiliki aturan baku khusus. Misal, seperti harus selalu bertemu dalam jadwal tertentu atau harus tag nama pasangan di media sosial masing-masing. Apa yang dilakukan dalam pacaran dilandasi oleh apa yang telah disepakati kedua belah pihak.
Pacaran tak semata-mata kegiatan berduaan dalam persoalaan makan malam atau nonton film. Bisa jadi sesuai kesepakatan kedua pihak, pacaran bisa diisi dengan kegiatan belajar bersama. Orang yang berpacaran juga tidak selamanya harus berpelukan atau bergandengan tangan, bisa saja mereka menjaga jarak satu sama lain karena merasa bukan mahram. Berpacaran juga bukan berarti harus bertemu setiap saat, bisa jadi mereka menjalani LDR alias hubungan jarak jauh satu sama lain.
Di samping pendapat sebagian orang yang menganggap pacaran banyak berdampak negatif, bagi sebagian lain pacaran berdampak positif. Lagi-lagi hal demikian mengungkapkan adanya berbagai sudut pandang tiap orang dalam menyikapi fenomena pacaran.
Jalan Kita yang Berbeda
Di ujung jalan kita menemui berbagai persimpangan. Ada orang yang menyikapi pacaran dengan sikap ‘anti’ yang fanatik, di samping mereka yang menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Selain itu, ada pula yang memilih untuk menjalani kehidupan asmara melalui pacaran, di samping mereka yang masih mempertanyakan makna pacaran itu sendiri.
Semestinya perbedaan antara mereka yang pro dan kontra atas fenomena pacaran bisa diibaratkan seperti Yin Yang dalam tradisi Tionghoa: bahwa setiap pertentangan dapat disikapi sebagai suatu keselarasan –sehingga dapat saling mengisi satu sama lain. Dengan demikian, tak perlu lagi dipertentangkan pemahaman di antara keduanya.
Untuk mereka yang berpacaran, tidak perlulah menebar kebucinan di depan jomblo –yang akan menimbulkan kengenesan. Sebaliknya, bagi mereka yang memilih tidak berpacaran, tidak perlu susah payah dengan khusyuk berdoa agar tiap malam minggu terjadi hujan badai –dengan harapan malming-nya mereka yang berpacaran jadi basah kuyup.
Bagi mereka yang memilih penjajakan melalui pacaran, selamat menjaga hati. Bagi mereka yang memilih pendekatan di luar pacaran, semoga cepat menemukan cinta sejati. Dan, bagi mereka yang masih mempertanyakan apa makna pacaran, semoga dapat cepat memahami. Dan untuk kamu yang sedang membaca ini –sambil menimbang-nimbang segala konsekuensi pacaran sambil duduk atau rebahan–, semoga dapat berbahagia dengan pilihan yang kamu yakini.
Penulis: Savero
Ilustrasi: Winda
Editor: Mustika