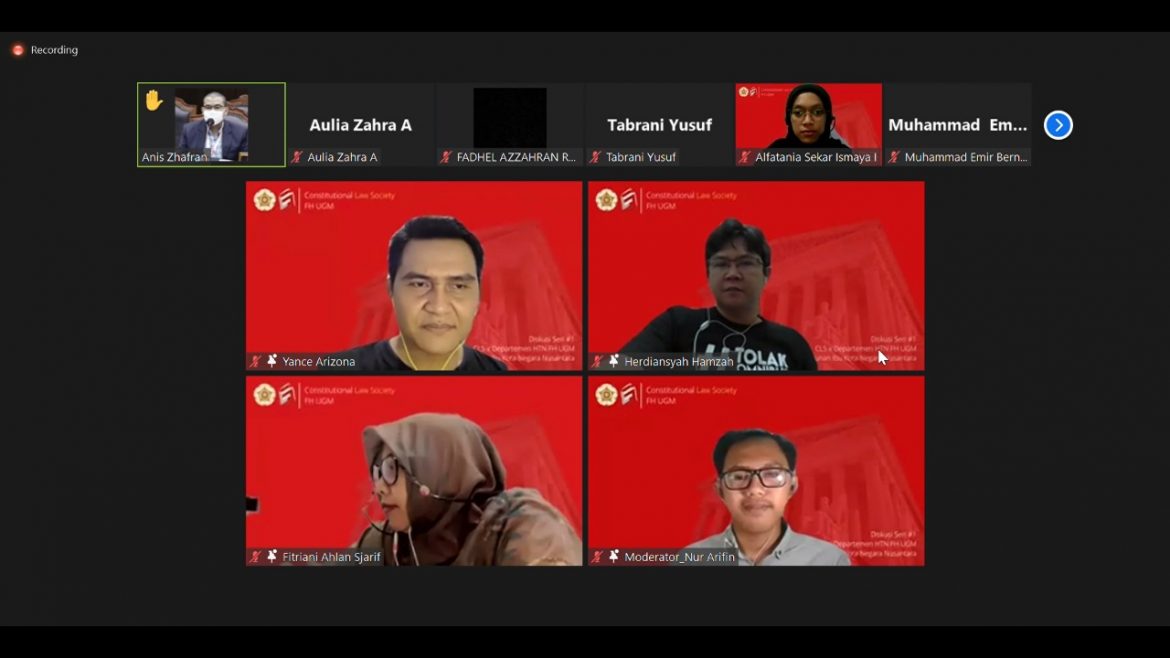Sabtu (26/2), melalui platform zoom meeting, Constitutional Law Society (CLS), sebuah komunitas penggiat isu-isu HTN di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengadakan diskusi akademis tentang pemindahan ibu kota baru Indonesia. Acara yang bertajuk “Arah Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara” tersebut berfokus membahas problematika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baik secara umum maupun berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan. Dengan menghadirkan tiga pembicara dari bidang akademisi, yakni Herdiansyah Hamzah (Dosen HTN Universitas Mulawarman), Fitriani Ahlan Sjarif (Dosen Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia), dan Yance Arizona (Dosen HTN Universitas Gadjah Mada), diskusi ini berjalan sukses diikuti kurang lebih 60 peserta.
Pada awal diskusi Herdiansyah Hamzah menjelaskan bahwa problematika pemindahan ibukota secara general sudah ada sejak 2019. Dalam paparannya, ia juga menyampaikan dua hal pokok. Pertama, apakah tepat pemindahan IKN di masa sekarang? Kedua, mengapa pilihan lokasi IKN di Kalimantan Timur?
Menjawab pertanyaan pertama, ia secara tegas menyampaikan pemindahan IKN sangatlah tidak tepat dan tidak rasional. Berangkat dari kondisi ekonomi Indonesia yang tengah porak-poranda akibat Covid-19, kemudian timbul pertanyaan darimanakah dana untuk pemindahan IKN ini didapat? Sebab, apabila dana diambil dari APBN tentu akan membebani postur anggarannya, sementara jika diambil dari investasi swasta akan memperlebar dikte asing terhadap Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan pembuatan UU IKN yang tergesa-gesa dan tanpa basis riset lokal mengakibatkan pemindahan IKN tidak memiliki legitimasi karena tidak adanya partisipasi masyarakat.
Sementara itu, untuk menjawab pertanyaan kedua, Hendriansyah, memaparkan data-data terkait lokasi pemindahan IKN, di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Dari data tersebut ia menyampaikan bahwa IKN pindah bukan pada ruang kosong tetapi pada wilayah yang sudah memiliki beragam persoalan. Khususnya persoalan ekologis sebagai dampak dari pemberian konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di area pemindahan IKN. Apabila dikalkulasikan keseluruhan luas konsesi tersebut mencapai 203.000 Ha atau setara dengan tiga kali luas Jakarta, dengan total 94 lubang bekas tambang yang sampai sekarang tidak ada kejelasan pemulihannya.
“Keseluruhan problem ekologis di Kalimantan Timur tidak bisa dijawab oleh pemindahan Ibu Kota Baru. Sebaliknya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur hanya menambah daftar dosa perusahaan-perusahaan yang selama ini beredar di Kalimantan Timur yang wilayah konstruksinya berdampak pada ruang hidup masyarakat,” tegas Hendriansyah sebagai penutup pemaparan materinya.
Diskusi ini turut mengupas terkait problematika Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 yang menjadi pondasi pemindahan ibu kota negara. Menilik dari kacamata pembentukan peraturan perundang-undangan, Fitriani Ahlan Sjarif, Dosen Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia menyorot terkait proses pembentukan Undang-Undang IKN yang kilat dengan hanya memakan waktu pembahasan selama 1 bulan 12 hari.
“RUU ini adalah salah satu Undang-Undang jalur fastrack,” ungkap Fitri dalam diskusi kemarin.
Fitri pun menegaskan jika sebenarnya tidak terdapat larangan tegas terkait pembentukan undang-undang jalur cepat. Namun, jika kita berbicara tentang suatu regulasi yang baik tentu terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, salah satunya adalah terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat. Menurut Fitri, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja yang minim partisipasi dan berujung mendapat penolakan masif.
“Terlalu berani jika baru saja putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dikeluarkan, pemerintah sudah menyusun Undang-Undang menggunakan jalur cepat lagi,” pungkasnya.
Meskipun DPR berdalih jika pihaknya sudah sangat transparan dalam menyampaikan tahapan proses pembentukan Undang-Undang IKN melalui website resminya, menurut Fitri hal tersebut tidaklah cukup.
“Yang disebut partisipasi bukan hanya menyampaikan tahapnya sudah sampai mana, tapi lebih pada apa yang DPR informasikan terhadap stakeholder yang terkena imbas, dan apa tanggapan stakeholder dan juga pemerintah terkait hal tersebut,” tegasnya ketika mengkritik transparansi Undang-Undang IKN.
Tak hanya berhenti sampai di situ, Fitri pun turut menganalisis jika pembentukan Undang-Undang yang ngebut tersebut berdampak pada tipisnya substansi Undang-Undang IKN yang hanya memiliki 44 pasal.
“Pemerintah memiliki will yang sangat besar membentuk suatu sistem baru yang sebenarnya tidak ruang hampa di sana, namun ternyata hanya terdapat 44 pasal,” imbuh Fitri.
Hal tersebut patut menjadi kekhawatiran bersama karena dapat berujung pada pendelegasian masal materi muatan yang seharusnya diatur melalui undang-undang terhadap peraturan pelaksana.
Ketika hampir seluruh pasal dalam Undang-Undang IKN ini memiliki kekurangan, menjadi menarik ketika membaca Bab IX terkait pemantauan dan peninjauan yang menurutnya terlalu berlebihan.
“Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jadi buat saya ini ada unsur politis agar DPR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU,” tutup Fitri.
Narasumber lain, Yance Arizona, Dosen HTN Universitas Gadjah Mada, turut mengelaborasi problematika konstitusional terkait Undang-Undang IKN ini. Ia menyoroti jika pasal jantung Undang-Undang IKN, yaitu Pasal 1 angka 2 tidak mengakomodir kedudukan Ibu Kota Negara secara lugas. Di mana, pasal tersebut menyatakan jika Ibu Kota Negara adalah satuan pemerintah daerah yang setingkat provinsi.
“Problemnya adalah ketika merujuk pada UUD NRI 1945, secara gramatikal setingkat provinsi berarti bukanlah provinsi,” ungkapnya.
Menurut analisisnya, Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 hanya menjelaskan jika NKRI hanya dibagi atas daerah setingkat provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten serta kota. Atas dasar itulah mengapa kedudukan Ibu Kota Negara versi Undang-Undang IKN masih sangat samar.
Yance pun juga menolak alasan DPR membenarkan kedudukan ibu kota negara dengan merujuk pada Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 terkait pemerintahan daerah yang bersifat khusus, seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, dan Papua.
“Konstruksi pasal a quo mengharuskan adanya daerah yang perlu diatur terlebih dahulu, baru diakui kekhususannya,” pungkas Yance.
Yang terjadi dalam kasus Ibu Kota Nusantara bukanlah pengakuan suatu pemerintahan daerah, tetapi pembentukan suatu daerah baru. Sehingga akan menjadi logika berpikir yang keliru jika mendalilkan legitimasi pemindahan ibu kota negara menggunakan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Piraunya penjelasan terkait kedudukan pasti ibu kota negara ini berbuntut pada ketidakjelasan kedudukan Kepala Otorita Negara yang diatur dalam Undang-Undang IKN.
Selain itu, Yance juga mengkritik kekosongan Badan Perwakilan Daerah dalam tatanan Ibu Kota Nusantara. Ia menganggap jika hal tersebut tidak sejalan dengan konstitusi mengenai satuan pemerintah daerah yang demokratis.
“Di IKN ini sepertinya memang dibuat bukan untuk satuan unit pemerintahan demokratis,” kritik tajam Yance terhadap sistem Ibu Kota Nusantara.
Dalam diskusi malam hari ini, terlihat banyak sekali kecacatan terkait pemindahan ibu kota negara baik dalam tataran yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Yance pun turut menduga jika pemindahan IKN merupakan bentuk perkembangan kapitalisme. Hal ini tampak jelas dari terkandungnya sifat kapitalis yang selalu membutuhkan ruang-ruang baru untuk eksploitasi dan akumulasi kekayaan dalam proses pemindahan ibu kota negara yang dapat menguntungkan orang-orang berkepentingan di sana.
Penulis : Aulia Zahra, Latif Putri
Penyunting : Afriza Nur Widyantari
Foto : Aulia Zahra