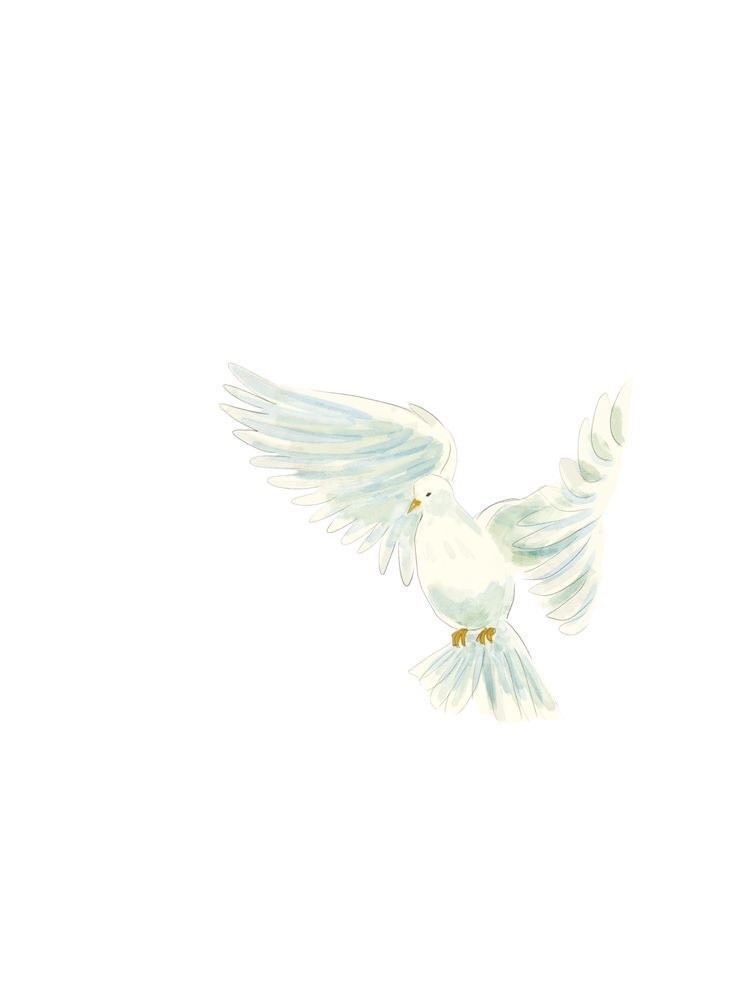Wanita itu datang kembali. Hari yang sama, tempat yang sama, jam yang sama, pakaian yang sama. Serba hitam. Dari yang kudengar, manusia selalu menganggap warna hitam adalah representasi dari sesuatu yang kelam, duka. Duka, bagaimana menjelaskannya? Ah, entah lah. Aku hanya tahu bahwa itu adalah hal yang menyedihkan. Mungkin, sama rasanya dengan tidak berhasil mendapatkan biji-bijian untuk makan di ladang yang tandus. Kali ini, wanita itu memakai payung yang senada dengan warna pakaiannya. Payung itu digunakan untuk melindungi tubuh rentanya dari tetesan air yang semakin deras. Aku tidak membutuhkan benda bernama payung itu. Tubuhku akan cepat kering jika aku terbang. Toh, aku juga dapat dengan mudah berlindung di balik daun pohon nan rimbun karena tubuhku cukup kecil.
Aku mengintip ke bawah dari tempatku duduk saat ini, yakni sebuah pohon yang tinggi. Oh, kali ini, wanita itu tidak sendiri. Ia ditemani beberapa manusia lain yang usianya tampak jauh lebih muda. Beberapa di antara mereka membawa poster yang memuat foto-foto manusia lain, entah siapa.
“Sudah lebih dari dua puluh tahun. dua puluh tahun! Dalam dua dekade ini, mereka masih belum mendapat keadilan!” Seorang manusia laki-laki berteriak. Suaranya masuk ke dalam sebuah benda besar yang berbentuk seperti corong. Tampaknya, benda itu membuat suara manusia terdengar lebih menggelegar.
Keadilan dan hak asasi manusia. Kata-kata itu selalu disuarakan wanita itu selama yang kuketahui. Apakah mereka tidak bosan meneriakkan kata-kata yang sama setiap minggunya? Apa sebenarnya arti dari kata tersebut? Mengapa mereka harus meneriakkan hal tersebut di depan bangunan megah ini? Apakah hak asasi manusia hanya untuk mereka saja? Apakah hewan juga memiliki hak asasi seperti itu? Hak asasi burung, mungkin?
Aku tak paham.
Mereka selalu berteriak ke arah bangunan tersebut. Mengapa bangunan itu sangat megah? Catnya putih bersih, bahkan buluku yang alami ini saja kalah putih dengannya. Aku pernah mencoba terbang memasuki bangunan tersebut. Kuakui, bangunan itu sangat megah, sungguh bertolak belakang dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Bahkan, jika aku terbang sedikit, aku akan menemukan sebuah perumahan yang terlihat kumuh di bantaran sungai.
“Tempo hari, Bapak Presiden sempat berkata akan menuntaskan kasus HAM, tetapi hingga akhir masa jabatannya, hanya beberapa saja yang beliau akui.” Wanita tua itu mulai berbicara.
Ah, hatiku tersayat menatap wanita tersebut. Tubuhnya sudah benar-benar renta, rambutnya hampir keseluruhannya berwarna putih. Mungkin, aku tak akan kaget jika suatu saat nanti beliau akan bertransformasi menjadi merpati putih sepertiku.
“Dan kini apa? Sang pelanggar HAM hendak memimpin negara ini?” seorang gadis muda berseru.
Mahasiswa. Katanya, mereka adalah mahasiswa, yakni anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Katanya, mereka mempunyai pemikiran yang kritis. Apakah seruan mereka kali ini adalah representasi dari kekritisan tersebut?
Entah lah, aku hanya burung. Mengapa aku selalu memperhatikan mereka? Padahal, hal itu sama sekali bukan urusanku. Aku memiliki kesempatan untuk menjelajah, terbang ke sana ke mari. Namun, tubuhku memilih untuk diam di sini, memperhatikan setiap detik perkumpulan itu bersuara.
Oh tunggu, aku baru menyadari sesuatu. Ibu itu selalu membawa foto seseorang. Seorang laki-laki, terlihat muda. Mungkin, seumuran dengan mahasiswa-mahasiswa yang menemani ibu itu.
Laki-laki itu tersenyum di foto. Senyum yang terlihat janggal. Ia tak terlihat santai maupun rileks. Aku bisa tahu bahwa ia ingin bebas. Mungkin, bebas seperti burung. Sepertiku. Di bawah fotonya, tertera sebuah tulisan. Aku tidak dapat membaca, tetapi kuasumsikan itu adalah nama laki-laki tersebut. Terdiri dari dua kata, sepertinya. Terlihat familiar. Seolah, aku pernah mengetahui hal tersebut entah di mana dan kapan.
“Sudah dua puluh tahun Langit Pranadipta menghilang. Lalu apa?”
Setelah ibu itu mengutarakan nama tersebut, mataku mendadak buram. Sepertinya, ada air yang masuk ke dalamnya. Aku menutup mata. ketika kubuka mata, semuanya terang. Ya, terang. Putih yang menyilaukan. Sedetik berikutnya, aku merasakan ada yang berbeda. Sayap. Sayapku hilang, tergantikan oleh tangan, tangan yang tak bisa kugerakkan. Pemandangan di hadapanku hanyalah langit.
Aku terbaring di tengah ladang, entah ladang apa, mungkin ilalang karena rasanya gatal. Kaki dan tanganku tak bisa digerakkan, seolah semua persendiannya telah dicopot. Aku dapat merasakan rasa asin serupa besi di mulutku. Ini pasti darah. Sakit. Saking sakitnya, aku tidak bisa merasakan apa pun. Apa ini? Mengapa aku tiba-tiba ada di sini?
Oh, aku paham. Ini pasti memori, ingatan yang entah dari mana datangnya. Mengapa tiba-tiba aku mengingatnya?
Ah, apa lah ini. Aku hanya bisa menatap ke atas, melihat langit biru dengan awan-awan putih tipis. Langit yang jauh di atas sana, bukan langit yang biasa menjadi arena permainanku, tempat di mana aku bisa terbang tinggi tanpa takut akan apa pun.
Ah, benar juga. Aku sangat ingin menjadi merpati di saat-saat terakhirku. Sembari menghitung detik-detik napasku mulai menghilang, aku berpikir, apakah Tuhan akan mengabulkan permintaan konyol itu? Menjadi merpati di kehidupan selanjutnya? Aku terkekeh. Apa pun yang akan terjadi, terjadilah. Dalam sekian menit setelahnya, detak jantungku perlahan menghilang, hanyut ditelan ingatan yang semakin mengabur.
Ketika aku membuka mata kembali, aku sudah kembali berada di antara kerumunan orang di depan bangunan megah tersebut. Di hadapanku, foto laki-laki itu terpampang jelas. Aku tersenyum dalam hati. Tentu saja, merpati tidak bisa tampak tersenyum. Namun, aku tahu. Aku tahu, di dalam diriku, ada jiwa manusia yang telah bebas. Jiwa anak muda itu. Anak semata wayang dari ibu yang telah puluhan tahun menagih keadilan dan janji.
Menunggu kepulangan anaknya.
Ah, seandainya saja ibu itu tahu bahwa anaknya selalu ada di sisinya. Setiap minggu, memperhatikan dari dahan tertinggi pohon terbesar di depan bangunan megah tersebut, dalam wujud burung merpati putih ini. Jika tahu soal itu, Ia tak akan khawatir lagi. Ia tak akan menantinya kembali. Meski telah berbeda wujud, tetapi jiwanya tetap sama.
Jiwa sang anak lelaki yang hilang sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu pada peristiwa paling bersejarah di negara ini.
fin.
by: Adventina Narda Maheswari